Fourth Reflection
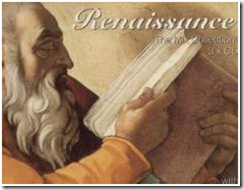 Asal mula adanya filsafat, adalah saat orang mulai memikirkan tentang segala hal, bukan tergantung pada keyakinan semata. Yang pada awalnya gempa bumi dianggap sebagai Dewa Bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya, sekarang dianggap sebagai peristiwa alam yang terjadi secara kausalitas, dan lain-lain. Keadaan ini terjadi pada bangsa yunani, mengapa bukan di bangsa lain? Karena pada bangsa yunani lah tidak ada larangan untuk berpikir seradix-radixnya, dan juga para pemikir didukung penuh oleh pemerintah yang berkuasa pada masanya. Ini diawali oleh pencarian unsur induk (arche) dari segala sesuatu yang ada di alam semesta (kosmogonis), Thales (sekitar 600 SM) mengemukakan bahwa air adalah arche, sedangkan Anaximander (sekitar 600 – 540 SM) mengatakan bahwa arche adalah sesuatu “yang tidak terbatas”, dan Anaximenes (sekitar 585 – 525 SM) berpendapat bahwa arche itu adalah udara, lain halnya dengan Herakleitos (±500 SM) yang berpendapat arche itu adalah api, sedangkan Pythagoras (sekitar 500 SM) mengatakan bahwa arche itu bilangan.
Asal mula adanya filsafat, adalah saat orang mulai memikirkan tentang segala hal, bukan tergantung pada keyakinan semata. Yang pada awalnya gempa bumi dianggap sebagai Dewa Bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya, sekarang dianggap sebagai peristiwa alam yang terjadi secara kausalitas, dan lain-lain. Keadaan ini terjadi pada bangsa yunani, mengapa bukan di bangsa lain? Karena pada bangsa yunani lah tidak ada larangan untuk berpikir seradix-radixnya, dan juga para pemikir didukung penuh oleh pemerintah yang berkuasa pada masanya. Ini diawali oleh pencarian unsur induk (arche) dari segala sesuatu yang ada di alam semesta (kosmogonis), Thales (sekitar 600 SM) mengemukakan bahwa air adalah arche, sedangkan Anaximander (sekitar 600 – 540 SM) mengatakan bahwa arche adalah sesuatu “yang tidak terbatas”, dan Anaximenes (sekitar 585 – 525 SM) berpendapat bahwa arche itu adalah udara, lain halnya dengan Herakleitos (±500 SM) yang berpendapat arche itu adalah api, sedangkan Pythagoras (sekitar 500 SM) mengatakan bahwa arche itu bilangan.
Pada abad pertengahan (400-1500 M), disebut sebagai zaman patristik dan skolastik. Filsafat pada abad ini dikuasai oleh pemikiran keagamaan (kristiani). Puncak filsafat ini adalah patristik (Lt. Patres = Bapa-Bapa Gereja) dan skolastik. Ajaran dari para Bapa Gereja ini adalah falsafi-teologis, yang pada intinya ingin memperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran-pikiran dalam diri manusia. Ajaran ini banyak dipengaruhi oleh Plotinos yang merupakan tokoh pendiri Neo Platonisme. Seluruh filsafatnya berkisar pada Tuhan sebagai yang satu, segala sesuatu berasal dari yang satu dan akan kembali kepadaNya. Zaman skolastik (sekitar tahun 1000 M), pengaruh Neo Platonisme diambil alih oleh Neo Aristotelian. Pemikiran-pemikirannya kembali dikenal dalam beberapa filsuf Yahudi maupun islam. Filsafatnya disebut skolastik (Lt. Scholasticus = guru) karena pada periode ini filsafat diajarkan dalam sekolah-sekolah biara dan universitas-universitas menurut suatu kurikulum yang baku dan berlaku internasional. Inti ajaran ini bertema pokok bahwa ada hubungan antara iman dan akal budi. Pada masa ini filsafat mulai ambil jarak dengan agama, dengan melihat sebagai suatu kesetaraan, bukan yang satu “mengabdi” terhadap yang lain.
Zaman renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan etika kebudayaan abad pertengahan menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang luas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan campur tangan Tuhan. Setelah renaissance mulailah zaman Barok, pada zaman ini tradisi rasionalisme ditumbuhkembangkan oleh Rene Descartes (1596-1650 M) yang menekankan pentingnya kemungkinan-kemungkinan akal budi (rasio) di dalam mengembangkan pengetahuan manusia. Pada abad kedelapan belas mulai memasuki perkembangan baru, dimana pemikiran manusia mulai dianggap telah “dewasa”. Filsuf-filsuf pada zaman ini disebut sebagai para empirikus, yang ajarannya menekankan bahwa suatu pengetahuan ada karena adanya pengalaman indrawi manusia (Lt. Empeira = pengalaman). Salah satu pendiri empirisme besar Inggris adalah D. Hume (1711-1776 M), dan di Jerman adalah Immanuel Kant (1724-1804 M). Secara khusus peranan Immanuel Kant adalah sebagai inspirator dan sekaligus sebagai peletak dasar fondasi ilmu, yakni mendamaikan pertentangan rasionalisme dengan empirisme dalam karya utamanya yang terkenal terbit tahun 1781 berjudul Critique of Pure Reason (Ing.). Dalam bukunya itu Kant memperkenalkan suatu konsepsi baru tentang pengetahuan. Pada dasarnya dia tidak mengingkari kebenaran pengetahuan yang dikemukakan oleh kaum rasionalisme maupun empirisme, yang salah apabila masing-masing dari keduanya mengkalim secara ekstrim pendapatnya dan menolak pendapat yang lainnya. Dengan kata lain memang pengetahuan dihimpun setelah melalui sistem penginderaan manusia, tetapi tanpa pikiran murni yang aktif tidaklah mungkin tanpa kategorisasi dan penataan dari rasio manusia. Menurut Kant, empirisme mengandung kelemahan karena anggapan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia hanyalah rekaman kesan-kesan (impresi) dari pengalamannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia merupakan hasil sintesis antara yang apriori (yang sudah ada dalam kesadaran dan pikiran manusia) dengan impresi yang diperoleh dari pengalaman. Bagi Kant yang terpenting bagaimana pikiran manusia memahami dan menafsirkan apa yang direkam secara empirikal, bukan bagaimana kenyataan itu tampil sebagai benda itu sendiri.
Filsafat abad kesembilan belas dan kedua puluh banyak bermunculan aliran-aliran baru dalam filsafat namun wilayah pengaruhnya lebih tertentu, akan tetapi justru menemukan format yang lebih bebas dari corak spekulasi filsafati dan otonom, aliran tersebut antara lain positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neo kantianisme, neo tomisme dan fenomenologi. Aliran positivisme yang digagas A. Comte (1798-1857 M) membagi pemikiran manusia menjadi tiga tahap, (1) teologis, (2) metafisis, (3) positif-ilmiah. Bagi era manusia dewasa (modern) ini pengetahuan hanya mungkin dengan menerapkan metode-metode positif ilmiah, artinya setiap pemikiran hanya benar secara ilmiah bilamana dapat diuji dan dibuktikan dengan pengukuran-pengukuran yang jelas dan pasti sebagaimana berat, luas dan isi suatu benda. Dari sinilah bangkit ilmu bidang seperti biologi, fisika, kimia, matematika, dll. Pada periode terkini (kontemporer) setelah aliran-aliran sebagaimana disebut di atas munculah aliran-aliran filsafat lain, misalnya : Strukturalisme dan Postmodernisme. Strukturalisme dengan tokoh-tokohnya misalnya Cl. Lévi-Strauss, J. Lacan dan M. Faoucault. Tokoh-tokoh Postmodernisme antara lain. J. Habermas, J. Derida. Kini oleh para epistemolog (ataupun dari kalangan sosiologi pengetahuan) dalam perkembangannya kemudian, struktur ilmu pengetahuan semakin lebih sistematik dan lebih lengkap (dilengkapi dengan, teori, logika dan metode sain), sebagaimana yang dikemukakan oleh Walter L.Wallace dalam bukunya The Logic of Science in Sociology. Dari struktur ilmu tersebut tidak lain hendak dikatakan bahwa kegiatan keilmuan/ilmiah itu tidak lain adalah penelitian (search and research).

Tidak ada komentar:
Posting Komentar